Dialah Mas’ud, yang mendapat julukan Blawong dari
KH. Zainuddin. Kelak dikemudian hari ia lebih dikenal dengan nama KH. Achmad
Djazuli Utsman, pendiri dan pengasuh I Pondok Pesantren Al-Falah, Ploso,
Kediri.
Diam-diam KH. Zainuddin memperhatikan gerak-gerik santri baru yang berasal dari Ploso itu. Dalam satu kesempatan, sang pengasuh pesantren bertemu Mas’ud memerintahkan untuk tinggal di dalam pondok.
“Co, endang ning pondok!”
“Kulo mboten
gadah sangu, Pak Kyai.”
“Ayo, Co…mbesok
kowe arep dadi Blawong, Co!”
Mas’ud yang
tidak mengerti apa artinya Blawong, hanya diam saja. Setelah tiga kali meminta,
barulah Mas’ud menurut perintah Kyai Zainuddin untuk tinggal di dalam bilik
pondok. Sejak itulah, Mas’ud kerap mendapat julukan Blawong.
Ternyata Blawong
adalah burung perkutut mahal yang bunyinya sangat indah dan merdu. Si Blawong
itu dipelihara dengan mulia di istana Kerajaan Bawijaya. Alunan suaranya
mengagumkan, tidak ada seorang pun yang berkata-kata tatkala Blawong sedang
berkicau, semua menyimak suaranya. Seolah burung itu punya karisma yang luar
biasa. Ia lahir di awal abad XIX, tepatnya tanggal 16 Mei 1900 M. Ia adalah
anak Raden Mas M. Utsman seorang Onder Distrik (penghulu kecamatan). Sebagai
anak bangsawan, Mas’ud beruntung, karena ia bisa mengenyam pendidikan sekolah
formal seperti SR, MULO, HIS bahkan sampai dapat duduk di tingkat perguruan
tinggi STOVIA (Fakultas Kedokteran UI sekarang) di Batavia.
Belum lama Mas’ud menempuh pendidikan di STOVIA, tak lama berselang Pak Naib, demikian panggilan akrab RM Utsman kedatangan tamu, KH. Ma’ruf (Kedunglo) yang dikenal sebagai murid Kyai Kholil, Bangkalan (Madura). “Pundi Mas’ud?” tanya Kyai Ma’ruf. “Ke Batavia. Dia sekolah di jurusan kedokteran,” jawab Ayah Mas’ud. “Saene Mas’ud dipun aturi wangsul. Larene niku ingkang paroyogi dipun lebetaken pondok (Sebaiknya ia dipanggil pulang. Anak itu cocoknya dimasukan ke pondok pesantren),” kata Kyai Ma’ruf. Mendapat perintah dari seorang ulama yang sangat dihormatinya itu, Pak Naib kemudian mengirim surat ke Batavia meminta Mas’ud untuk pulang ke Ploso, Kediri. Sebagai anak yang berbakti ia pun kemudian pulang ke Kediri dan mulai belajar dari pesantren ke pesantren yang lainnya yang ada di sekitar karsidenan Kediri.
Mas’ud mengawali masuk pesantren Gondanglegi di Nganjuk yang diasuh oleh KH. Ahmad Sholeh. Di pesantren ini ia mendalami ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Qur’an, khususnya tajwid dan kitab Jurumiyah yang berisi tata bahasa Arab dasar (Nahwu) selama 6 bulan.
Setelah menguasai ilmu Nahwu, Mas’ud yang dikenal sejak usia muda itu gemar menuntut ilmu kemudian memperdalam pelajaran tashrifan (ilmu Shorof) selama setahun di Pondok Sono (Sidoarjo). Ia juga sempat mondok di Sekarputih, Nganjuk yang diasuh KH. Abdul Rohman. Hingga akhirnya ia nyantri ke pondok yang didirikan oleh KH. Ali Imron di Mojosari, Nganjuk dan pada waktu itu diasuh oleh KH. Zainuddin. KH. Zainuddin dikenal banyak melahirkan ulama besar, semacam KH. Wahhab Hasbullah (Pendiri NU dan Rais Am setelah KH. Hasjim Asy’ari), Mas’ud yang waktu itu telah kehabisan bekal untuk tinggal di dalam pondok kemudian mukim di langgar pucung (musala yang terletak tidak jauh pondok). Selama di Pondok Mojosari, Mas’ud hidup sangat sederhana. Bekal lima rupiah sebulan, dirasa sangat jauh dari standar kehidupan santri yang pada waktu rata-rata Rp 10,-. Setiap hari, ia hanya makan satu lepek (piring kecil) dengan lauk pauk sayur ontong (jantung) pisang atau daun luntas yang dioleskan pada sambal kluwak. Sungguh jauh dikatakan nikmat apalagi lezat.
Di tengah
kehidupan yang makin sulit itu, Pak Naib Utsman, ayah tercinta meninggal. Untuk
menompang biaya hidup di pondok, Mas’ud membeli kitab-kitab kuning masih kosong
lalu ia memberi makna yang sangat jelas dan mudah dibaca. Satu kitab kecil
semacam Fathul Qorib, ia jual Rp 2,5,-(seringgit), hasil yang lumayan untuk
membiayai hidup selama 15 hari di pondok itu. Setelah empat mondok di Mojosari,
Mas’ud kemudian dijodohkan dengan Ning Badriyah putri Kyai Khozin, Widang,
Tuban (ipar Kyai Zainuddin). Namun rupa-rupanya antara Kyai Khozin dan Kyai
Zainuddin saling berebut pengaruh agar Mas’ud mengajar di pondoknya.
Di tengah
kebingungan itulah, Mas’ud berangkat haji sekaligus menuntut ilmu langsung di
Mekkah. H. Djazuli, demikian nama panggilan namanya setelah sempurna menunaikan
ibadah haji. Selama di tanah suci, ia berguru pada Syeikh Al-‘Alamah
Al-Alaydrus di Jabal Hindi. Namun, ia di sana tidak begitu lama, hanya sekitar
dua tahun saja, karena ada kudeta yang dilancarkan oleh kelompok Wahabi pada
tahun 1922 yang diprakasai Pangeran Abdul Aziz As-Su’ud. Di tengah
berkecamuknya perang saudara itu, H. Djazuli bersama 5 teman lainnya berziarah
ke makam Rasulullah SAW di Madinah. Sampai akhirnya H. Djazuli dan
kawan-kawannya itu ditangkap oleh pihak keamanan Madinah dan dipaksa pulang
lewat pengurusan konsulat Belanda. Sepulang dari tanah suci, Mas’ud kemudian
pulang ke tanah kelahirannya, Ploso dan hanya membawa sebuah kitab yakni
Dalailul Khairat. Selang satu tahun kemudian, 1923 ia meneruskan nyantri ke
Tebuireng Jombang untuk memperdalam ilmu hadits di bawah bimbingan langsung
Hadirotusy Syekh KH. Hasjim Asya’ri.
Tatkala H.
Djazuli sampai di Tebuireng dan sowan ke KH. Hasjim Asya’ri untuk belajar,
Al-Hadirotusy Syekh sudah tahu siapa Djazuli yang sebenarnya, ”Kamu tidak usah
mengaji, mengajar saja di sini.” H. Djazuli kemudian mengajar Jalalain, bahkan
ia kerap mewakili Tebuireng dalam bahtsul masa’il (seminar) yang
diselenggarakan di Kenes, Semarang, Surabaya dan sebagainya. Setelah dirasa
cukup, ia kemudian melanjutkan ke Pesantren Tremas yang diasuh KH. Ahmad
Dimyathi (adik kandung Syeikh Mahfudz Attarmasiy). Tak berapa lama kemudian ia
pulang ke kampung halaman, Ploso.
Sekian lama
Djazuli menghimpun “air keilmuan dan keagamaan”. Ibarat telaga, telah penuh.
Saatnya mengalirkan air ilmu pegetahuan ke masyakrat. Dengan modak tekad yang
kuat untuk menanggulangi kebodohan dan kedzoliman, ia mengembangkan ilmu yang
dimilikinya dengan jalan mengadakan pengajian-pengajian kepada masyarakat Ploso
dan sekitarnya. Hari demi hari ia lalui dengan semangat istiqamah menyiarkan
agama Islam. Hal ini menarik simpati masyakarat untuk berguru kepadanya. Sampai
akhirnya ia mulai merintis sarana tempat belajar untuk menampung murid-murid
yang saling berdatangan. Pada awalnya hanya dua orang, lama kelamaan berkembang
menjadi 12 orang. Hingga pada akhir tahun 1940-an, jumlah santri telah
berkembang menjadi sekitar 200 santri dari berbagai pelosok Indonesia. Pada
jaman Jepang, ia pernah menjabat sebagai wakil Sacok (Camat). Di mana pada
siang hari ia mengenakan celana Goni untuk mengadakan grebegan dan rampasan
padi dan hasil bumi ke desa-desa. Kalau malam, ia gelisah bagaimana melepaskan
diri dari paksaan Jepang yang kejam dan biadab itu. Kekejaman dan kebiadaban
Jepang mencapai puncaknya sehingga para santri selalu diawasi gerak-geriknya,
bahkan mereka mendapat giliran tugas demi kepentingan Jepang. Kalau datang
waktu siang, para santri aktif latihan tasio (baris berbaris) bahkan pernah
menjadi Juara se-Kecamatan Mojo. Tapi kalau malam mereka menyusun siasat untuk
melawan Jepang. Demikian pula setelah Jepang takluk, para santri kemudian
menghimpun diri dalam barisan tentara Hisbullah untuk berjuang.
Selepas perang
kemerdekaan, pesantren Al-Falah baru bisa berbenah. Pada tahun 1950 jumlah
santri yang datang telah mencapai 400 santri. Perluasan dan pengembangan pondok
pesantren, persis meniru kepada Sistem Tebuireng pada tahun 1923. Suatu sistem
yang dikagumi dan ditimba Kyai Djazuli selama mondok di sana. Sampai di akhir
hayat, KH. Ahmad Djazuli Utsman dikenal istiqomah dalam mengajar kepada
santri-santrinya. Saat memasuki usia senja, Kyai Djazuli mengajar kitab
Al-Hikam (tasawuf) secara periodik setiap malam Jum’at bersama KH. Abdul Madjid
dan KH. Mundzir. Bahkan sekalipun dalam keadaan sakit, beliau tetap mendampingi
santri-santri yang belajar kepadanya. Riyadloh yang ia amalkan memang sangat
sederhana namun mempunyai makna yang dalam. Beliau memang tidak mengamalkan
wiridan-wiridan tertentu. Thoriqoh Kyai Djazuli hanyalah belajar dan mengajar
“Ana thoriqoh ta’lim wa ta’allum,”katanya berulangkali kepada para santri. Hingga
akhirnya Allah SWT berkehendak memanggil sang Blawong kehadapan-Nya, hari Sabtu
Wage 10 Januari 1976 (10 Muharam 1396 H). Beliau meninggalkan 5 orang putra dan
1 putri dari buah perkawinannya dengan Nyai Rodliyah, yakni KH. Achmad
Zainuddin, KH. Nurul Huda, KH. Chamim (Gus Miek), KH. Fuad Mun’im, KH. Munif
dan Ibu Nyai Hj. Lailatus Badriyah. Ribuan umat mengiringi prosesi pemakaman
sosok pemimpin dan ulama itu di sebelah masjid kenaiban, Ploso, Kediri.
Konon, sebagian anak-anak kecil di Ploso, saat jelang kematian KH. Djazuli, melihat langit bertabur kembang. Langit pun seolah berduka dengan kepergian ‘Sang Blawong’ yang mengajarkan banyak keluhuran dan budi pekerti kepada santri-santrinya itu.

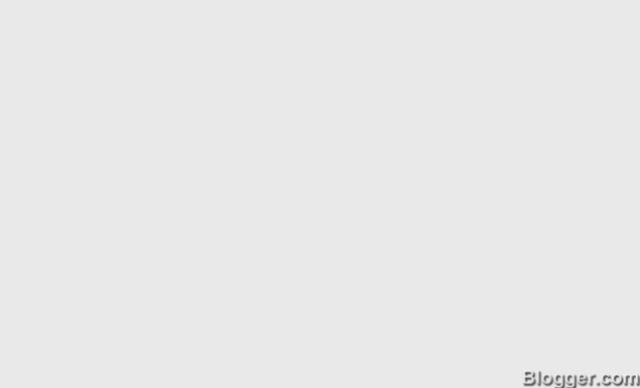

Post a Comment Blogger Facebook